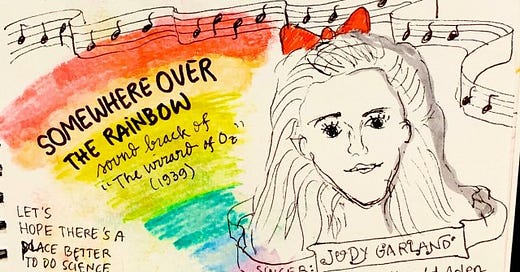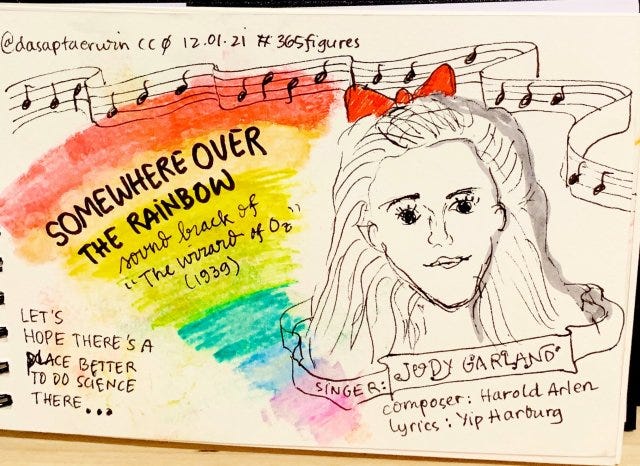How to Promote contributorship and data sharing to cultivate research integrity
Bagaimana cara mempromosikan kontribusi dan berbagai data untuk menumbuhkan integritas riset (di Indonesia). Akan dipresentasikan di acara 2022 ACSE Conference Aug 21st, 2022.
Penulis: Dasapta Erwin Irawan (ITB) dan Juneman Abraham (Binus)
Situasi pengukuran riset di Indonesia sangat bergantung kepada metrik. Pemerintah melalui berbagai regulasi tingkat nasional dan pimpinan perguruan tinggi lebih fokus mengukur luaran berupa makalah. Terbitnya makalah digunakan sebagai indikator proksi utama kinerja riset yang mana ini seringkali bukan kasus yang terjadi.
Integritas riset masih belum memperoleh prioritas, terbukti dari peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, yang terbit akhir tahun 2021 namun belum disosialisasikan pada tingkat nasional hingga saat ini. Kami mempromosikan contributionship bukan sekedar authorship. Authorship adalah bagian dari contributionship dan bukan sebaliknya. Walaupun CREDIT saat ini telah menjadi standar dalam pemasukan makalah, tetapi authorship tetap menjadi norma penghargaan.
Kami meninjau Permendikbudristek. Pada Pasal 9(d) dan Pasal 10(4), yang menyatakan ketentuan tentang kepengarangan atau kepenulisan yang tidak sah. Kepengarangan tidak sah berarti seorang penulis tidak berkontribusi aktif dalam kepenulisan sebuah karya ilmiah, maupun menyumbangkan gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan terkait.
Kami berharap kalimat tersebut merupakan “celah segar” untuk mempromosikan Contributorship, karena “menggabungkan diri sebagai pengarang” dalam Permendikbudristek tersebut dapat didasarkan atas peran aktif dalam penyusunan naskah atau peran lain yang belum didefinisikan secara operasional.
Terlebih lagi, Rancangan Peraturan Kepala LIPI (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional) Pasal 32 menyatakan bahwa "status kontributor untuk kegiatan kolaborasi dinilai berdasarkan peran kontribusi Peneliti (contributorship)" dapat menjadi indikator kinerja peneliti.
Ini berarti peran kepengarangan dapat merujuk kepada 14 peran kontribusi dalam panduan CREDIT.Praktik berbagi data (data sharing) adalah hal kedua yang menjadi fokus kami. Data juga membangun integritas riset. Analisis tidak akan dapat dilakukan tanpa data, karena itu data harus selalu melekat di dalam berbagai luaran riset. Bukan sekedar tabel data di dalam makalah, tetapi juga data mentah yang dapat digunakan ulang oleh peneliti lainnya.
Data akan sangat berkaitan dengan peneliti yang merancang sistematika pengambilan data, merancang perangkat percobaan, orang yang mengambil data di lapangan atau melakukan eksperimen, juga lembaga yang mendanainya. Yang sudah pasti tidak berkaitan adalah data sebagai hak milik, terutama untuk riset yang didanai negara. Berbagi data dapat memacu perkembangan ilmu pengetahuan lebih jauh dan lebih cepat.
Percakapan internasional telah mengarahkan data sebagai luaran riset yang independen. Ini berarti data perlu dan harus dapat dibagikan ulang kepada peneliti lainnya, dengan penyitiran.
Masalah kronis di Indonesia adalah belum mengakarnya budaya berbagi data, yang ditinjukkan dengan (1) Misinformasi tentang “kode etik penelitian” – seolah berbagi data akan melanggar kode etik, (2) Persepsi kehilangan (loss) atau kerugian, khususnya untuk data yang tidak dapat diperoleh dengan mudah (seperti data dari pedalaman di Indonesia), dan (3) Kebingungan untuk menentukan tingkat sensitivitas data.Saat ini di Indonesia etika dalam riset identik dengan komisi etik yang hanya mengkaji etika penggunaan data berkaitan dengan manusia/data personal dan hewan.Padahal dalam etika, pegangan tertinggi adalah nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati, sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbudristek Pasal 2(2).
Segenap tindakan riset perlu senantiasa dibandingkan dari waktu ke waktu kompatibilitasnya dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, “lolos kaji etik” bukanlah tujuan utama. Hal ini agar kita tidak terjebak pada praktik “menyiasati pelembagaan etik riset dan publikasi”, misalnya menutup-nutupi praktik nir-etika demi pemenuhan sertifikasi dan/atau akreditasi kampus serta demi memperoleh pendanaan dari sponsor yang memiliki keinginan kuat untuk mengendalikan publikasi hasil penelitian demi kepentingan egosentriknya.
Pembekalan etika riset sangat dibutuhkan para dosen atau peneliti pemula sebagai bagian pengenalan integritas riset untuk dapat menanggulangi tiga masalah penting di bawah ini.
Kami menemukan tiga masalah besar dalam mengenalkan integritas atau etika riset dan publikasi di Indonesia, yang mengakibatkan etika belum terintegrasi sepenuhnya dalam praktik-praktik riset/akademik dosen dan peneliti Indonesia.
Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan pendekatan ilmuwan Indonesia kepada riset yang: (1) kebarat-baratan, (2) hitam-putih (black or white, all or none), dan (3) mengutamakan penghukuman.
Masalah pertama Pendekatan secara literal yang dibawa oleh para alumnus universitas barat. Mereka membawa secara bulat-bulat literasi etika riset dan publikasi dari almamaternya ke Indonesia. Mereka membandingkan praktik yang mereka saksikan, pelajari, dan alami di tempat belajarnya dengan praktik di Indonesia, lalu menyatakan kekecewaan mereka bahwa budaya akademik di Indonesia tidak seberetika budaya akademik di luar negeri.
Lebih lanjut mereka menyelenggarakan berbagai seminar dan lokakarya dengan sebuah ambisi, hendak “membabat habis” praktik-pratik nir-etika pada dosen dan peneliti di Indonesia. Yang mereka lupakan adalah hal yang kami sebut sebagai “kesabaran dalam memahami konteks Indonesia”.
Berbagai kajian dan studi sudah menemukan dengan jelas bahwa kepekaan kultural sangat dibutuhkan dalam memahami dan mengelola praktik yang dianggap “tak berintegritas” di Barat namun yang “seperti ditoleransi” di Timur (seperti di Indonesia). Dalam hal plagiarisme, misalnya, telah dilakukan studi empiris dan kajian oleh Adiningrum dan Kutieleh (2011), Nash (2018), dan TurnItIn (2017) yang menemukan bahwa cultural sensitivity dibutuhkan dalam menyikapi kasus-kasus etika.
Masalah kedua Pendekatan yang terkait dengan pendekatan dalam masalah pertama. Pemahaman yang universal hanya akan menghasilkan satu sudut pandang. Kita menjadi lupa bahwa etika bukan persoalan “boleh atau tidak boleh”, “hitam atau putih”, melainkan pada hakikatnya etika merupakan sebuah “pertanggungjawaban mengapa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral”.
Ambil contoh, ilmuwan yang terbiasa dengan satu dimensi pandangan kemungkinan besar akan terkejut menyimak (1) Telaah Aydin Mohseni (2020) - yang memiliki minat luas terhadap filsafat Timur-Tengah - yang justru mempertanggungjawabkan pandangannya bahwa "HARKing (hypothesizing after results are known) can actually be good", (2) Refleksi Andrew Gelman (2017) yang memberikan telaah kritis bahwa terminologi “p-hacking” perlu digugat karena menghadirkan sebuah prasangka bahwa peneliti yang melakukannya memiliki intensi sadar untuk berbuat curang (cheating). Kedua contoh ini menunjukkan bahwa upaya mengatasi permasalahan “krisis replikasi” yang diantaranya diatribusikan pada praktik HARKing dan p-hacking tidak akan mengalami kemajuan, khususnya di Indonesia, apabila kita tidak mampu mempertimbangkan kompleksitas yang melatarbelakangi praktik-praktik tersebut.
Masalah ketiga Pendekatan penghukuman (punitif, retributif) seringkali terdengar dalam perbincangan ketika sebuah kasus bernuansa etika “mencuat”. Pada 2020, kami sudah menyerukan, “Jangan mengadili sebelum kita sendiri melakukan upaya sistematis peliterasian mengenai praktik-praktik yang dianggap questionable”. Rupanya, ini sangat sejalan dengan advis dari COPE (Committee on Publication Ethics), “COPE would always advocate educational rather than punitive action.”Langkah-langkah pembekalan dini untuk para dosen dan peneliti pemula perlu menghindari tiga pendekatan yang menjadi masalah di atas.
Pemberian wawasan tentang etik ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum tahap sarjana, yang saat ini baru dipenuhi dengan konten-konten terkait publikasi, yang berada di bagian hilir dari sebuah riset.
Penyampaiannya perlu menyisipkan contoh-contoh riil yang terjadi di dunia penelitian dari hulu ke hilir. Cara COPE menyampaikan kasus dalam bentuk tanya jawab dapat diadaptasi.